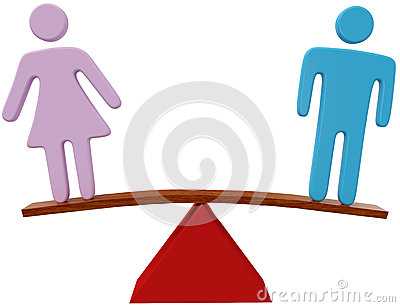
Nama merupakan sebuah identitas menjadi salah satu bukti
yang menjelaskan sebuah keberadaan/eksistensi sesuatu. Nama orang Bali
Merupakan sebuah kebudayaan luhur yang kaya akan makna yang tersirat bila kita
sebagai generasi penerus mampu menterjemahkan warisan-warisan budaya tersebut
secara bijak.
Bicara mengenai bali adalah bicara mengenai
pengetahuan yang di manifestasi menjadi berbagai karya dan budaya. Pragmatisme
merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan eksistesialisme orang bali. Kenapa
demikian? Pragmatisme merupakan sebuah cabang filsafat yang menyatakan bahwa
kebenaran pengetahuan adalah kebermanfaatannya (Practice), artinya tedensi kebenaran
pengetahuan adalah aksiologinya bukan ontology maupun epistomologinya. Tentu
hal ini bukan sekadar spekulasi penulis, namun ini merupakan sebuah kebenaran,
sebagai contoh orang bali tidak/belum membudayakan membaca Kitab Suci “Wedha”,
namun inti-inti ajaran wedha itu di bentuk menjadi sebuah ritual-ritual suci
agama yang lebih menekankan sisi aksiologi pengetahuan wedha tersebut. Bukan
berangkat dari hal itu saja masih banyak contoh-contoh lain yang mendukung
argument-argument penulis, salah satunya adalah makna tersirat dibalik penamaan
orang-orang Bali.
Tentu kita sudah mengetahui, arti-arti penamaan
orang bali secara tersurat seperti Wayan atau “Wayahan” = Lebih Tua, Made atau “Madya”= Tengah, Nyoman yang secara etimologis berasal dari kata
"uman" yang bermakna “sisa” atau “akhir, Ketut yang merupakan kata
serapan “Ke+tuut”- ngetut artinya
mengikuti atau mengekor. Tapi dalam artikel kali ini, kita tidak akan membahas
makna tersurat dalam penamaan orang bali, namun lebih dari itu ialah makna
tersirat yang terkandung di dalamnya.
Apakah kira-kira makna tersirat di balik penamaan
orang-orang bali tersebut?. Salah satu identitas orang bali adalah penamaannya.
Kebanyakan orang bali mempunyai nama depan yang sama sesuai dengan urutan
kelahirannya. Nama depan putu, kadek, nyoman dan ketut merupakan nama-nama umum
yang dipakai oleh orang-orang bali. Selain nama-nama tersebut juga ada
nama-nama seperti Desak, Anak Agung, Ida Bagus yang merupakan nama-nama
wangsa/bangsawan bukan kasta (Imperialisme
Hinduism melalui sistem kasta bukan “Varna”). Sebenarnya kalau dikaji lebih
dalam di balik penamaan orang-orang bali seperti wayan, dkk terkandung prinsip
Egaliterism (kesetaraan). Tentu dalam hal ini spesifikasinya adalah kesetaraan
sosial. Anak Agung Gede…. merupakan contoh kesamaan tersebut. Baik dari golongan bangsawan maupun yang
bukan golongan bangsawan tetap mengindahkan nama-nama umum orang bali
tersebut.
Tentu timbul sebuah pertanyaan? Kalau dari penamaan
orang bali tersebut tersirat paham egaliterism (Dalam hindu istilah ini identik
dengan Tatwam Asi)? Lantas darimana asumsi bahwa sistem kasta itu ada
dalam budaya bali? Tentu untuk membahas sistem kasta kita harus membahas
sejarah hindu secara komprehensif, semenjak kedatangan bangsa arya yang
membaur/mengusir sebahagian bangsa dravida hingga kedatangan imperialism
inggris dan visi misionarisnya di India. Banyak kalangan intelektual
hindu yang menentang adanya sistem kasta, karna kalau mengacu pada kitab suci
sistem kasta tidak ditemukan akan tetapi yang ada hanyalah sistem Varna
(Pengelompokkan sosial berdasarkan pencahariannya). Sistem kasta mulai populer
ketika India kedatangan kaum imperialisme inggris. Banyak pembengkokan-pembengkokan
sejarah dan juga penerjemahan kitab-kitab suci secara sempit (Hidden
Vision). Kasta identik dengan statifikasi sosial yang negative, di
dalam sistem kasta itu terdapat kelas sosial yang terbuang (Paria), dimana kaum
ini lahir sebagai akibat perkawinan antara kelas-kelas sosial yang berbeda
tingkat dalam tingkatan sistem kasta tersebut (yang sebenarnya tidak diperbolehkan kasta yang satu menjalin hubungan
lebih dengan kasta yang lain), tentu hal ini merupakan bentuk penjajahan
kelas, yang identik dengan Kaum Berpunya dan Kaum Tidak Berpunya. Apakah di
bali sistem kasta itu berlaku? Jawaban ini dapat teman-teman baca pada artikel
(http://inputbali.com/sejarah-bali/sejarah-adanya-kasta-di-bali).
Di akhir penghujung, Sebagai generasi penerus yang
mewarisi sebuah budaya yang agung ini, maka tentu kita harus menjaga kebudayaan
itu, menambah kekayaan tersebut bukan malah sebaliknya enggan menggunakan atau
melanjutkan kebudayaan adiluhung (“) yang secara langsung mengikis
kebudayaan itu secara perlahan. “Mengatasnamakan peradaban namun mengikis
kebudayaan”.
